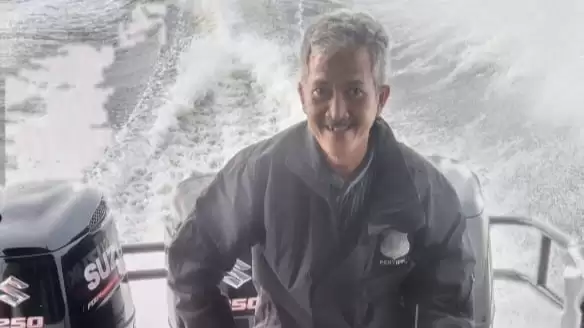Langit Riau malam itu terasa pekat, sama pekatnya dengan rongga dada Arya. Aroma masakan yang seharusnya membangkitkan selera makan, kini terasa seperti abu di lidahnya. Di meja makan, hanya ada suara denting sendok dari tiga anaknya: Lintang (10), Bima (7), dan si bungsu Aira (3). Rani, istrinya, tidak ada. Lagi-lagi.
"Papa, Mama belum pulang?" tanya Lintang, mata kecilnya memancarkan kerinduan yang ditahan.
Arya memaksa seulas senyum. "Mama sedang ada urusan kerjaan mendadak, Sayang. Besok pasti Mama bacakan cerita sebelum tidur."
Bohong. Arya tahu itu bohong. Rani, wanita yang dulu ia perjuangkan dari nol saat ia hanya seorang freelancer desain grafis dan Rani seorang admin, kini menjelma menjadi orang asing. Rumah yang mereka bangun dari cicilan, impian yang mereka rajut dari tawa kecil anak-anak, terasa seperti istana pasir yang baru saja dihantam ombak.
Semua berawal enam bulan lalu, saat Rani memutuskan kembali bekerja di sebuah perusahaan properti besar. Awalnya, Arya bangga. Ia mendukung penuh. Namun, kebanggaan itu perlahan digantikan oleh kecurigaan yang menusuk. Panggilan telepon yang selalu dimatikan saat ia mendekat, parfum baru yang terlalu mahal, dan alasan lembur yang semakin sering.
Puncaknya adalah malam minggu tiga minggu lalu. Arya menemukan sebuah kartu nama yang terselip di saku jaket Rani. Nama yang tercetak di sana adalah Bramantyo Adiwangsa, lengkap dengan gelar "Direktur Utama" yang mentereng dan foto profil yang memancarkan aura kekuasaan.
Saat Arya menanyakannya, Rani tidak mengelak, tidak juga membela diri. Matanya yang dulu selalu memancarkan kehangatan saat menatapnya, kini dingin, kosong, dan dipenuhi rasa bersalah yang tersembunyi.
"Aku... aku hanya lelah, Mas," bisiknya saat itu, suaranya parau. "Lelah dengan semua ini. Aku mau lebih dari sekadar dapur dan anak-anak."
Lebih? Arya memejamkan mata. Apa yang kurang? Ia bekerja keras hingga larut malam. Ia menjemput anak-anak. Ia menjadi suami dan ayah terbaik yang ia tahu. Demi Tuhan, mereka bahkan baru saja merencanakan perjalanan umroh tahun depan.
"Lebih seperti apa, Ran? Jabatan tinggi? Kemewahan?" Suara Arya bergetar. "Apakah moralitas kita, sumpah kita di depan Tuhan, cinta kita, bisa ditukar dengan semua itu? Kemana perginya moralitas hingga dosa kamu langgar?"
Rani hanya menangis, air matanya jatuh tanpa suara. Tangisan itu bukan permohonan maaf, melainkan ratapan penyesalan atas pilihan yang sudah ia ambil. Pilihan untuk menikmati gemerlap dunia yang ditawarkan Bramantyo, seorang pria mapan yang jauh lebih matang, yang menjanjikan kehidupan yang tidak pernah bisa Arya berikan.
Musnahnya Impian
Beberapa hari setelah pengakuan itu, Arya menyaksikan kehancuran rumah tangganya dalam diam. Rani pergi. Ia tidak membawa banyak barang, hanya koper berisi pakaian barunya dan sebuah janji kosong untuk sering menengok anak-anak.
Arya duduk di tepi ranjang. Ia memeluk baju tidur Rani yang masih menyimpan sedikit aroma vanila. Bau yang ia kenal selama lebih dari sepuluh tahun. Ia memeluknya erat, seperti memeluk kenangan terakhir sebelum semuanya terkikis habis.
Ia teringat saat mereka berdua bergandengan tangan menatap rumah kecil impian mereka yang masih setengah jadi. "Nanti, kita akan penuhi rumah ini dengan tawa anak-anak, Ya," kata Rani saat itu, matanya bersinar bahagia.
Sekarang, tawa itu ada, tetapi pelengkapnya telah hilang. Arya melihat foto pernikahan mereka di dinding. Senyum Rani begitu tulus, begitu suci. Air matanya menetes, membasahi bingkai foto itu.
Kerna nafsu dunia hingga agama dinodai.
Kalimat itu bergaung di benaknya. Bukan hanya Rani yang melanggar, tetapi ia juga merasa gagal menjaga benteng rumah tangga mereka. Kegagalan ini terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Ia tidak hanya kehilangan istri, ia kehilangan sahabat, ibu dari anak-anaknya, dan masa depan yang ia yakini akan abadi.
Malam itu, Arya memeluk ketiga anaknya di ranjang. Ia menceritakan dongeng, tetapi suaranya tercekat. Ia mencium kening Lintang, Bima, dan Aira, berharap cinta tulus mereka bisa menyembuhkan luka yang menganga.
"Papa, kenapa mata Papa merah?" tanya Aira dengan polos.
Arya hanya menggeleng. Ia menarik napas panjang. Ia harus kuat. Demi anak-anak ini. Ia harus menemukan sisa-sisa semangatnya yang sudah dihancurkan oleh nafsu dunia yang membutakan.
Ia menatap langit-langit, berharap menemukan jawaban atas pertanyaan abadi: Apakah harus terus begini? Apakah kehancuran ini adalah akhir dari segalanya?
Jawabannya adalah tidak. Arya tahu ia tidak boleh menyerah. Rani telah memilih jalannya, jalan yang ia tahu akan penuh duri dan kesesatan. Tapi Arya, sebagai ayah, harus memilih jalan lain: jalan pemulihan, jalan pengampunan, dan jalan untuk membangun kembali impian yang musnah, kini hanya berempat.
Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya mengering. Di balik luka ini, ia berjanji akan mencari kembali moralitas yang hilang, bukan di mata orang lain, tapi di dalam jiwanya sendiri, agar ia bisa berdiri tegak dan menjadi mercusuar bagi anak-anaknya. Sebuah janji yang ia ukir di atas puing-puing rumah tangganya yang hancur.
Catatan Redaksi
(Cerita ini dimaksudkan untuk membangkitkan empati dan menggambarkan kehancuran yang ditimbulkan oleh pengkhianatan dalam rumah tangga.)